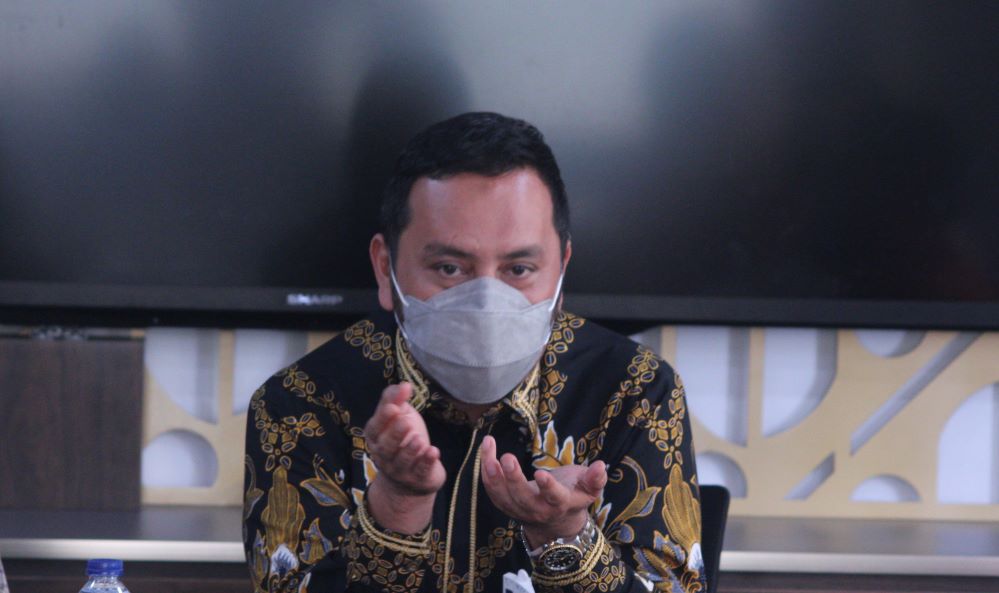Oleh Willy Aditya
Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
BEBERAPA minggu lalu, seorang kerabat lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Dia dinyatakan lulus dan diterima di Fakultas Kedokteran sebuah perguruan tinggi negeri (PTN). Ada kebanggaan di satu sisi namun terjadi kegalauan di sisi yang lain. Kebanggaan lahir karena sang kerabat mampu “menaklukkan†fakultas paling bergengsi dalam dunia perguruan tinggi, sementara rasa galau muncul karena soal biaya segera membuat keluarga kerabat berpikir tujuh keliling.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pendidikan kedokteran berbiaya mahal. Kesiapan peserta didik diukur bukan hanya dari segi kapasitas intelektual melainkan juga modal besar. Sialnya, bahkan setelah selesai pun seseorang yang dinyatakan lulus tidak bisa langsung disebut sebagai ahli Perlu proses dan dana lanjutan agar seorang lulusan pendidikan kedokteran dapat menjalankan profesinya.
Banyak kalangan akhirnya menilai wajar jika praktik seorang dokter akhirnya dinilai begitu eksklusif dan berbiaya tinggi. Demikian pula terhadap rumah sakit yang seakan terjerumus dalam logika bisnis sebagaimana lazimnya. Meski masih kita temui fenomena semacam Dr Lie Dharmawan yang menyajikan kesehatan berbiaya murah (bahkan gratis), namun keumuman menyampaikan kepada kita tentang relasi yang kuat antara profesi dokter dengan logika ongkos yang mahal.
Kritik atas Pendidikan Kedokteran
Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 ternyata memang memberi legitimasi atas formal dan panjangnya masa pendidikan hingga legalitas profesi seorang dokter. Sejumlah aturan yang dikandungnya menunjukkan panjangnya birokrasi yang berbanding lurus dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Secara kuantitatif, ribuan calon dokter akhirnya tidak dapat menjalankan profesinya akibat terjegal syarat legal formal yang diminta. Secara kualitatif, ke mana arah pendidikan kedokteran Indonesia sebenarnya, telah menjadi pertanyaan besar bagi bangsa ini.
Alan Bleakley (2015), seorang dokter sekaligus profesor Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Humanis, mengatakan bahwa tradisi pedagogis pendidikan kedokteran berperan penting dalam menciptakan dokter di masa depan yang bertanggung jawab atas gagalnya demokratisasi dunia medis. Hilangnya sensitivitas, sensibilitas, dan akhirnya empati dalam praktik medis hasil pendidikan kedokteran, menjadi titik kritis yang menurutnya harus kembali dihidupkan melalui mekanisme institusionalisasi lembaga pendidikan kedokteran.
Apa yang disampaikan Bleakley juga pernah disampaikan jauh hari oleh William Osler (1849-1919), seorang profesor di John Hopkins Hospital yang memperkenalkan program residensi dalam kurikulum pendidikan kedokteran yang digunakan sampai saat ini. Osler membayangkan dunia medis sebagai dunia dengan humanisme yang mendalam di mana praktik medis adalah sebuah seni, bukan perdagangan. Dunia medis adalah sebuah panggilan di mana hati dan kepala diuji secara setara.
Tradisi kedokteran humanis, menurut Bleakley, kini telah menggeser praktik medis lama di mana semuanya berpusat pada hirarki otoritas yang berada di tangan dokter. Kedokteran humanis menekankan perhatiannya kepada pasien dan kesalinghubungan internal profesi di dalam proses klinis.
Langkah demikian ini disadari Bleakley sebagai tantangan yang bersifat politis. Dia menegaskan, kedokteran humanis yang disebutnya adalah dokter untuk keadilan sosial, yang memperlakukan pasien sebagai manusia utuh yang memiliki hak kemanusian dan kewarganegaraan. Lebih jauh, kedokteran humanis mengarahkan tujuannya demi mengatasi ketimpangan kesehatan dan menyiapkan akses layanan kesehatan secara setara.
Community Oriented
Dalam perkembangannya, dunia medis internasional saat ini tengah berlomba mengkoneksikan antara pendidikan kedokteran dengan situasi kemasyarakatan. Rachel Ellaway dkk dari Ontario School of Medicine, Canada, mengatakan, pendidikan kedokteran yang berikatan dengan masyarakat (community engaged) kini dipraktikkan di banyak negara di dunia. Hal ini diyakini dapat menghasilkan kualitas dan keterikatan yang lebih baik bagi program pendidikan kedokteran serta meningkatkan akuntabilitas sosial lembaga pendidikan terkait. Konsep keterikatan yang demikian ini merupakan pengembangan dari konsep sebelumnya dalam balutan terminologi “berorientasi kemasyarakatanâ€.
Strasser (2010) mendefinisikan “orientasi kemasyarakatan†(community oriented) sebagai upaya mengarahkan kurikulum pendidikan kedokteran ke dalam topik-topik kesehatan masyarakat. Dia mendefinisikan, “berbasis kemasyarakatan†sebagai setting situasi masyarakat dalam kurikulum pendidikan kedokteran namun tidak secara langsung mengikatkan diri untuk mendesain dan menyelenggarakan kurikulumnya di dalam internal masyarakat. Sementara, “keterikatan kemasyarakatan†(community engaged) didefinisikan sebagai keterikatan erat pendidikan kedokteran secara langsung dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pengalaman peserta didik.
Pembelajaran tentang endemi di dalam pendidikan kedokteran di berbagai negara menjadi kontekstual dalam pembahasan ini. Mempelajari isu endemi penyakit dalam situasi yang berikatan langsung dengan masyarakat tentu akan menghasilkan hal yang berbeda dengan hanya mempelajarinya dari masyarakat (community based) maupun belajar untuk masyarakat (community oriented). Hal inilah yang kita bisa lihat dari kurikulum pendidikan kedokteran Kuba (Suarez, Sacacas dkk, 2008) dan kini telah menjadi isu penting di berbagai negara seperti Jepang, Australia, Canada, dan berbagai negara lainnya.
Arah Pendidikan Kedokteran Kita
Pandemi Covid-19 dengan gamblang menyampaikan tentang begitu besarnya kelemahan kita sebagai bangsa dalam mempersiapkan sumber daya kesehatan. Kita menyaksikan pemusatan sumber daya kesehatan yang begitu timpang seiring ketimpangan ekonomi yang terjadi antardaerah.
Saat ini, ada 89 fakultas kedokteran yang tersebar di 38 PTN dan 51 PTS. Sayangnya, dari angka tersebut kita masih menghadapi masalah persebaran dokter di Tanah Air. UU No 20 Tahun 2013 dalam kenyataannya belum mampu menjawab masalah tersebut. Ia bahkan disebut telah melahirkan sejumlah persoalan baru hingga ada kebutuhan mendesak untuk merevisinya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah rumusan arah pendidikan kedokteran kita.
Mungkin masih terlalu jauh untuk menerapkan kurikulum pendidikan kedokteran yang menganut community-engaged medical education. Namun setidaknya, kita bisa mulai berkomitmen untuk mengembalikan spirit humanisme dalam pendidikan kedokteran kita. Spirit yang menempatkan kemanusiaan sebagai yang utama dalam dunia medis dan kesehatan nasional kita. Dan itu bisa dimulai dalam rumusan UU Pendidikan Kedokteran.
Sejumlah masalah sudah diindentifikasi dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pendidikan Kedokteran yang kini berada di tangan Badan Legislasi DPR RI. Sejumlah usulan dan pemikiran yang beraras pada semangat kemanusiaan telah dirumuskan. Mulai dari rasio dokter dengan penduduk, program-program afirmasi, hingga demokratisasi pendidikan kedokteran nasional.
Inilah yang menjadi tantangan dalam upaya merevisi UU Pendidikan Kedokteran. Tantangan yang tentunya bukan sekadar mengubah pasal-pasal semata, melainkan upaya membangun kesepahaman bersama akan pentingnya merestorasi Pancasila sebagai jiwa dalam pendidikan kedokteran kita.
Konstitusi mengamanatkan kepada pemegang kebijakan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam pemaknaannya yang umum, kesejahteraan merujuk pada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam kerangka inilah revisi UU Pendidikan Kedokteran dilaksanakan guna menjawab tantangan konstitusi dan semangat zamannya. [*]